Text
Cerita dari negeri inklusi
Pergantian kepemimpinan era Soekarno ke Soeharto tidak hanya menyisakan sejarah kelam Indonesia tetapi juga mengubah 180 derajat paradigma pembangunan yang terjadi di Indonesia. Soekarno dengan Permesta (Perencanaan Pembangunan Semesta) yang membangun dari demokrasi terpimpin dengan mengutamakan pada jiwa bangsa yang merdeka dan mandiri sebagai suatu bangsa. Di era Soeharto semua diubah dengan paradigma pembangunan yang mengedepankan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Paradigma ini mengabaikan jiwa manusia Indonesia yang merdeka kembali pada mental ketergantungan pada negara-negara maju (pemenang perang dunia ke-II).
Pada era tersebut dimulailah babak rekontruksi sosial dimana perbedaan, kekayaan tradisional kita bahkan kearifan lokal nusantara nyaris tidak diberi tempat dan bahkan disingkirkan atas nama pembangunan (teori W.W Rostow1)) yang dijalankan oleh regim pada saat itu. Pembangunan sosial, politik, ekonomi, dan budaya Indonesia dirancang mengikuti kriteria Barat modern, yaitu bahwa kesuksesan ekonomi diciptakan mengikuti pemikiran kapitalisme. Paradigma ini ternyata berdampak sangat parah terhadap kondisi bangsa Indonesia dimana sentralisasi pembangunan tidak menumbuhkembangkan nilai-nilai tradisonal sebagai pengetahuan dan kekayaan intelektual bangsa ini, melainkan membunuh apa yang menjadi ciri khas kepribadian bangsa Indonesia.
Di era itu pula penghancuran identitas kultural—termasuk Masyarakat Adat, hak-hak tradisionalnya dan basis-basis sumber daya alam—dilakukan secara terstruktur dan masif oleh negara atas nama pembangunan tadi. Padahal sejarah mencatat bahwa bangsa Indonesia lahir justru di atas alas budaya, agama, suku, dan nilai-nilai adat-istiadat yang berbeda-beda. Sebagaimana semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara kita, Garuda Pancasila, yaitu Bhinneka Tunggal Ika.
Pengalaman dari penerapan teori pertumbuhan ekonomi yang berharap adanya trickle down effect,2) tidak serta-merta dapat memperbaiki taraf hidup seluruh rakyat Indonesia. Emil Salim yang juga merupakan salah seorang arsitek ekonomi Orde Baru mengakui bahwa pembangunan Indonesia selama 30 tahun terakhir sama sekali tidak menuju kepada pembangunan yang berkelanjutan. Melainkan bergantung pada ekstraksi dan ekploitasi Sumber Daya Alam (SDA),3) yang keberhasilannya pun hanya dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya investasi asing. Sementara dampak yang ditimbulkannya, seperti kerusakan lingkungan, masyarakat di sekitar lokasi ekstrasi dan eksploitasi SDA yang tereksklusi yang menjadi korban, sama sekali tak diperhatikan.
Karenanya tentu tidak mudah memperbaiki keadaan yang sudah terlanjur. Dan kehadiran Program Peduli yang diinisiasi oleh Pemerintah Indonesia bersama organisasi masyarakat sipil beberapa tahun silam merupakan satu upaya untuk menjangkau setiap warga negara yang tadinya mengalami peminggiran, yang menjadi korban pembangunan dan lemah posisinya secara sosial, ekonomi, politik dan budaya tadi. Baik yang karena perbedaan ras, agama, etnik, kelas sosial, posisi geografis, maupun karena mereka masih menjalankan adat istiadat warisan nenek moyangnya. Salah satunya adalah kelompok masyarakat adat lokal dan terpencil yang masih bergantung pada SDA5).
Program Peduli dirancang khusus untuk membantu kelompok yang tereksklusi tadi. Yaitu sebagai upaya agar tidak ada ada yang tertinggal, dan memastikan terjadinya inklusi sosial bagi kelompok marginal dan terabaikan. Sehingga mereka pun bisa mendapatkan hak-haknya sebagaimana warga negara lainnya, khususnya pada akses layanan dasar (termasuk bantuan sosial), pemberdayaan dan penerimaan sosial serta turut mendorong kebijakan yang inklusif.
Inklusi sosial disini dapat diartikan sebagai sebuah proses membangun hubungan sosial dan menghormati individu serta komunitas, sehingga mereka yang termarginalkan dan mengalami prasangka dapat berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan, kehidupan ekonomi, sosial, politik, budaya, serta memiliki akses dan kontrol yang sama atas sumber daya (untuk memenuhi kebutuhan dasar) dalam rangka menikmati standar kesejahteraan yang dianggap layak di dalam kelompok masyarakat yang bersangkutan.5)
Dalam kerangka besar itulah Program Peduli yang dilaksanakan Kemitraan/Partnership Governace Reform sejak tahun 2014 dengan bekerjasama 14 CSO lokal di 13 Provinsi dan 21 Kabupaten/kota di Indonesia—berupaya mendorong terjadinya inklusi sosial di dalam semua wilayah program kerjanya.
Dalam pelaksanaan program tersebut, tak cuma data dan angka yang berseleweran dalam keseharian dan kehidupan para pelaku program ini, tetapi juga beraneka ragam kisah dan cerita turut merwarnai. Mulai dari cerita fasilitator lapangan yang horor, yang membuat terpingkal-pingkal sampai kisah yang membuat berlinangan air mata. Termasuk kisah inspiratif dari orang-orang kecil yang tentu tak pernah diperhitungkan di negeri bernama Indonesia.
Karena itu cerita dalam buku ini mencoba merekam jejak mereka, yaitu para pelaku inklusi sosial, para kader, champion lokal, dan orang-orang marginal yang selama ini tereksklusi dan tersingkirkan oleh proses pembangunan tadi.
“Jika kau melihat bintang-bintang di malam hari, itulah mereka. Terlihat tidak bergerak, tetapi itu hanya di matamu. Sejatinya mereka sedang beraktivitas. Bintang-bintang di Boti, baik yang berkonde maupun yang tidak, sama-sama berjuang menerangi kampung dengan sinarnya yang redup...,” tulis Denimars Sailana dari Yayasan Tanpa Batas ketika berkisah tentang Suku Adat Boti yang hidup di dekat perbatasan Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan Timor Leste.
Orang-orang yang diceritakan dalam buku ini tak ubahnya bintang kecil yang timbul tenggelam di cakrawala malam tanpa ada yang menghiraukannya. Mereka adalah orang-orang yang sepi dari apresiasi dan publikasi. Media-media nasional terlalu disibukan oleh antrian iklan dan berita politik, sementara sosial media lebih banyak mem-posting hoaks, khutbah-khutbah dan sumpah-serapah dari pada kisah-kisah kemanusian.
Maka kehadiran buku yang berisi 23 cerita ini adalah sebuah ikhtiar kami dalam menghadirkan kisah-kisah manusia yang selama ini luput dari perbincangan para politikus ibu kota, para pelaku media dan gosip di kafe-kafe Jakarta. Cerita ini berasal dari 15 pelosok desa/kelurahan di 10 provinsi, dan ditulis oleh 9 pelaku Program Peduli-Kemitraan.
Buku ini juga adalah sebuah moment, sebuah serpihan saja dari realitas rakyat kecil yang tengah terhuyung-huyung berusaha menjadi bagian dari mimpi kemakmuran negeri bernama Indonesia. Ceritanya dikemas dalam cara tutur sederhana, dimana kami berharap buku ini juga dapat menjadi ‘jembatan literasi’ yang menghubungkan secara sadar antara yang membangun dengan yang dibangun, antara yang tereksklusi dengan yang mengekslusi, dan antara yang membaca dan yang diceritakan. Bahwa kita adalah sama-sama warga negara, sama-sama pemilik sah republik ini, dan sama-sama anak bangsa yang berhak mendapatkan pelukan hangat ibu pertiwi, tanpa terkecuali.
Ketersediaan
Informasi Detail
- Judul Seri
-
-
- No. Panggil
-
398.2 ALE c
- Penerbit
- Jakarta : Kemitraan., 2018
- Deskripsi Fisik
-
342 hlm.: 21 cm
- Bahasa
-
Indonesia
- ISBN/ISSN
-
9786021616741
- Klasifikasi
-
398.2
- Tipe Isi
-
text
- Tipe Media
-
-
- Tipe Pembawa
-
-
- Edisi
-
-
- Subjek
- Info Detail Spesifik
-
-
- Pernyataan Tanggungjawab
-
-
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

 Karya Umum
Karya Umum  Filsafat
Filsafat  Agama
Agama  Ilmu-ilmu Sosial
Ilmu-ilmu Sosial  Bahasa
Bahasa  Ilmu-ilmu Murni
Ilmu-ilmu Murni 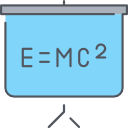 Ilmu-ilmu Terapan
Ilmu-ilmu Terapan 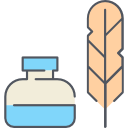 Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 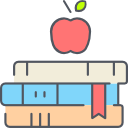 Kesusastraan
Kesusastraan  Geografi dan Sejarah
Geografi dan Sejarah